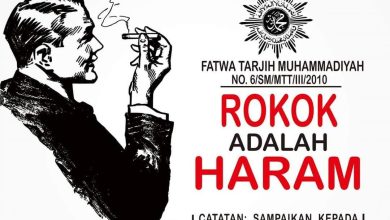Tafsir Progresif Muhammadiyah dalam Lintasan Iman

Tafsir Progresif Muhammadiyah dalam Lintasan Iman
Oleh : T.H. Hari Sucahyo (Penggagas Lingkar Studi Adiluhung dan Kelompok Studi Pusaka AgroPol
tinggal di Semarang)
PWMJATENG.COM – Sebagai seorang Katolik yang tumbuh dalam tradisi liturgi, sakramen, dan spiritualitas yang terstruktur, perjumpaan saya dengan pemikiran-pemikiran dalam tubuh Muhammadiyah membuka cakrawala yang tak saya duga sebelumnya. Muhammadiyah, sebuah organisasi Islam modernis yang didirikan pada 1912 oleh KH Ahmad Dahlan, ternyata menyimpan semangat intelektual dan pembaruan yang sebanding dengan dinamika dalam Gereja Katolik, khususnya pasca Konsili Vatikan II (Haedar Nashir, 2015).
Dalam lintasan iman saya, yang lebih sering dipenuhi dengan simbol-simbol ritual dan keheningan kontemplatif, membaca tajdid atau pembaruan yang diusung Muhammadiyah seperti mendengar gema yang akrab, meski dari arah yang berbeda. Tajdid dalam konteks Muhammadiyah bukan sekadar modernisasi dalam pengertian teknis atau struktural. Ia adalah proses rekontekstualisasi pemahaman keagamaan yang berakar pada nalar, wahyu, dan realitas sosial (Syamsul Anwar, dalam Suara Muhammadiyah, 2008). Ini bukan hal yang ringan.
Di banyak kesempatan, saya menyaksikan bagaimana para intelektual Muhammadiyah berani menafsirkan ulang teks-teks klasik Islam dengan keberanian metodologis yang langka. Di tengah kecenderungan formalisme dalam banyak diskursus keagamaan, pendekatan Muhammadiyah justru memikat karena tidak anti-tradisi, namun kritis terhadap stagnasi pemikiran. Di sinilah saya melihat gema dari apa yang dalam tradisi Katolik disebut sebagai aggiornamento, sebuah seruan untuk memperbarui Gereja agar relevan dengan zaman, sebagaimana dikumandangkan oleh Paus Yohanes XXIII (John W. O’Malley, 2008).
Dalam salah satu kuliah umum yang pernah saya ikuti, seorang pemikir Muhammadiyah menjelaskan tentang pentingnya rasionalitas dalam memahami agama. Baginya, iman tanpa akal dapat terjebak dalam dogmatisme yang membutakan, sementara akal tanpa iman bisa melahirkan kekeringan spiritual. Kalimat itu langsung mengingatkan saya pada ajaran Santo Thomas Aquinas yang menyatakan bahwa “grace perfects nature”, anugerah ilahi menyempurnakan akal budi manusia, bukan meniadakannya.
Kemiripan semacam ini tidak hanya menyentuh secara intelektual, tapi juga menyentuh secara spiritual, karena saya merasa sedang berdialog dalam bahasa iman yang universal: bahasa pencarian makna di tengah zaman yang terus berubah. Apa yang menarik dari tafsir progresif Muhammadiyah adalah keberaniannya untuk tetap setia pada sumber wahyu, namun terbuka terhadap tafsir baru yang dibutuhkan oleh konteks zaman.
Baca juga, Ketika Amal Jadi Konten: Apakah Riya Bisa Tervalidasi secara Digital?
Misalnya dalam isu-isu sosial seperti hak perempuan, kesehatan reproduksi, kepedulian terhadap kemiskinan struktural, atau bahkan relasi antaragama, saya melihat keberanian yang jernih untuk tidak terpaku pada literalitas teks, tapi menggali substansi nilai-nilai etikanya. Pendekatan ini mengingatkan saya pada prinsip sensus fidelium dalam tradisi Katolik, yaitu kepekaan umat akan kehendak Allah yang kadang melampaui kerangka resmi institusi. Muhammadiyah, meski lahir dalam konteks Islam, menghidupi prinsip serupa, yakni keterlibatan aktif umat dalam merespons zaman dengan iman yang hidup.
Sebagai penonton dari luar, saya tentu tidak hendak menggurui atau menilai dari dalam. Namun dalam pengamatan saya, ada kekuatan epistemologis yang khas dalam tafsir progresif Muhammadiyah. Pertama, keberanian untuk menggali makna maqashid syariah (tujuan hukum Islam) sebagai dasar berpikir, bukan sekadar tekstualitas sempit (Jasser Auda, 2008). Kedua, keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan modern sebagai mitra tafsir, bukan ancaman. Ketiga, komitmen sosial yang mengakar bahwa agama tak boleh berhenti pada diskursus, tapi harus menjadi praksis.
Ini menunjukkan bahwa nalar dalam Muhammadiyah bukan sekadar alat bantu memahami wahyu, tapi juga kompas etika yang menggerakkan transformasi sosial. Saya menyadari bahwa tidak semua tradisi keagamaan sanggup menjalani transformasi semacam itu tanpa resisten internal. Dalam Gereja Katolik sendiri, dinamika pasca-Konsili Vatikan II juga tidak mulus. Ada tarik-ulur antara kelompok progresif dan konservatif, antara pembaruan dan kekhawatiran kehilangan identitas. (Massimo Faggioli, 2012)
Maka dari itu, ketika melihat bagaimana Muhammadiyah secara konsisten mengembangkan tafsir yang kontekstual tanpa kehilangan akar teologisnya; saya merasakan suatu kematangan spiritual yang patut dihargai. Bukan karena mereka ‘modern’ secara budaya, tetapi karena mereka tetap setia pada panggilan moral untuk menjadikan agama sebagai kekuatan pembebas, bukan pembelenggu.
Sebagai umat Katolik, saya belajar dari Muhammadiyah tentang pentingnya menjadikan nalar sebagai mitra iman. Bahwa spiritualitas yang membumi harus berdialog dengan realitas sosial, bukan sekadar melangit dalam doa-doa pribadi. Dalam dunia yang kian plural dan kompleks, cara beragama yang progresif dan reflektif menjadi kebutuhan bersama.
Di titik inilah saya merasa bahwa lintasan iman kita, meskipun berbeda jalur, bisa saling menyinari. Mata Katolik saya mungkin melihat dengan cara yang berlainan, tapi ia tak bisa mengabaikan cahaya yang terpancar dari semangat tajdid itu. Di balik perbedaan bahasa, simbol, dan institusi, saya percaya bahwa kita sedang menuju Tuhan yang sama, Tuhan yang menginginkan kita terus belajar, bertumbuh, dan mencintai.
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha