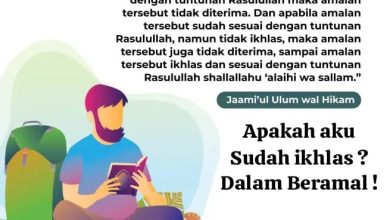Monetisasi Konten Digital dalam Timbangan Islam: Antara Cuan dan Keberkahan

PWMJATENG.COM – Perkembangan dunia digital telah membuka peluang besar bagi siapa saja untuk menjadi kreator konten sekaligus pelaku ekonomi digital. Platform seperti YouTube dan TikTok menjadi wajah utama dari transformasi ini. Di balik popularitasnya, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana Islam memandang praktik monetisasi konten yang kini menjadi sumber pendapatan utama bagi banyak orang?
YouTube, misalnya, memiliki lebih dari 2,7 miliar pengguna global dan lebih dari 140 juta di Indonesia. TikTok tidak kalah masif, dengan sekitar 1,7 miliar pengguna global dan lebih dari 100 juta di Indonesia. Pendapatan global YouTube tahun 2024–2025 diperkirakan mencapai 47 miliar dolar AS, dengan kreator global seperti MrBeast yang memiliki 361 juta pelanggan—lebih dari jumlah penduduk Indonesia.
Pendapatan dari platform ini tak main-main. Rata-rata kreator lokal Indonesia bisa memperoleh Rp10.000 hingga Rp50.000 per seribu tayangan (views). Untuk kreator global, angkanya berkisar antara 0,125 hingga 1 USD per seribu views. Pendapatan ini berasal dari berbagai skema monetisasi seperti AdSense, Super Chat, Membership, dan YouTube Shopping. Sementara TikTok memiliki Creator Rewards, TikTok Pools, Live Gifts, hingga Affiliate Marketing.
Dalam konteks ini, monetisasi didefinisikan sebagai proses mengubah konten digital menjadi sumber penghasilan. Namun, sebagaimana disampaikan dalam pengajian oleh salah satu tokoh Muhammadiyah, monetisasi bukanlah keharusan. “Monetisasi adalah pilihan,” ungkapnya. “Kalau tidak dimonetisasi, konten tetap bisa digunakan untuk dakwah, edukasi, bahkan hiburan.”
Namun, pertanyaan penting muncul: apakah praktik monetisasi ini halal? Dalam kaidah fikih, muamalah pada dasarnya bersifat mubah (boleh), sebagaimana kaidah الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم “Hukum asal segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya.”
Namun demikian, pendekatan fikih legal-formal saja tidak cukup. Perlu dilihat lebih dalam melalui lensa maqashid syari’ah—tujuan syariat Islam yang berpijak pada kemaslahatan. Artinya, apakah praktik monetisasi membawa manfaat atau justru mudarat? Jika membawa maslahat, maka ia dapat ditempatkan dalam koridor syariat.
Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern memiliki pedoman yang cukup kokoh. Majelis Tarjih dan Tajdid telah merumuskan Etika Bisnis Islam dalam Himpunan Putusan Tarjih (HPT) Jilid 3. Meskipun belum sepenuhnya praktis, dokumen ini menjadi pijakan penting dalam menyikapi isu muamalah kontemporer.
Baca juga, Etika Bercanda dalam Islam: Ora Waton Guyon
Etika bisnis dalam HPT disusun dalam tiga bagian besar: dasar pemikiran, asas, serta niat dan tolok ukur. Dalam dasar pemikiran, ditegaskan bahwa seluruh harta adalah milik Allah, sebagaimana firman-Nya:
وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ
“Berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang telah Dia berikan kepadamu” (QS. An-Nur: 33).
Dengan demikian, manusia hanyalah pemegang amanah. Harta bukan semata alat pemuas duniawi, tetapi sarana meraih rida Allah dan kebahagiaan akhirat.
Selain itu, Islam sebagai rahmatan lil ‘alamin tidak membatasi nilai-nilainya pada urusan ibadah mahdhah saja, tetapi juga mencakup semua aspek kehidupan termasuk bisnis digital. Etika bisnis dalam Islam tidak berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam tiga fondasi: akidah, syariah, dan akhlak.
Asas-asas etika bisnis yang diangkat dalam HPT meliputi: tauhid, amanah, kejujuran (shidq), keadilan (‘adalah), kesucian (‘iffah), kerja sama (ta‘awun), kemaslahatan (maslahah), kerelaan (taradhi), dan akhlak mulia (akhlaq al-karimah). Nilai-nilai ini menjadi rambu dalam menentukan apakah sebuah aktivitas digital layak dimonetisasi atau tidak.
Sementara itu, bagian niat dan tolok ukur dalam HPT menggarisbawahi larangan praktik yang mengandung unsur haram seperti:
- Gharar (ketidakjelasan)
- Jahalah (ketidaktahuan transaksi)
- Maysir (spekulasi atau judi)
- Riba
- Kezaliman
- Dharar (mudarat)
- Kecurangan dan penipuan
Monetisasi yang menampilkan konten-konten merusak moral, berita palsu, atau eksploitasi emosi, dapat digolongkan melanggar prinsip-prinsip di atas. Maka, seorang Muslim harus mempertimbangkan tidak hanya peluang ekonomi, tetapi juga dampak moral dan sosial dari kontennya.
Sebagaimana disampaikan dalam pengajian itu, “Duit itu penting, tapi bukan segalanya. Jangan sampai karena mengejar monetisasi, kita melupakan keberkahan dan nilai-nilai Islam.”
Monetisasi konten digital memang membuka peluang besar dalam era ini. Namun, bagi seorang Muslim, pertanyaan paling mendasar bukan hanya “berapa penghasilan dari YouTube?” tetapi “apakah konten ini membawa maslahat, dan apakah ia diridhai Allah?”
Dalam kerangka ini, monetisasi bukan sekadar strategi menghasilkan uang, tetapi juga ladang dakwah dan amal saleh—jika dijalankan sesuai dengan etika Islam.
Kontributor : Marsya
Ass Editor : Ahmad; Editor : M Taufiq Ulinuha