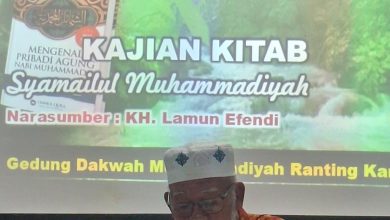Generasi Alpha dan Kamus Bahasa Baru: Antara Evolusi Digital dan Kemerosotan Literasi
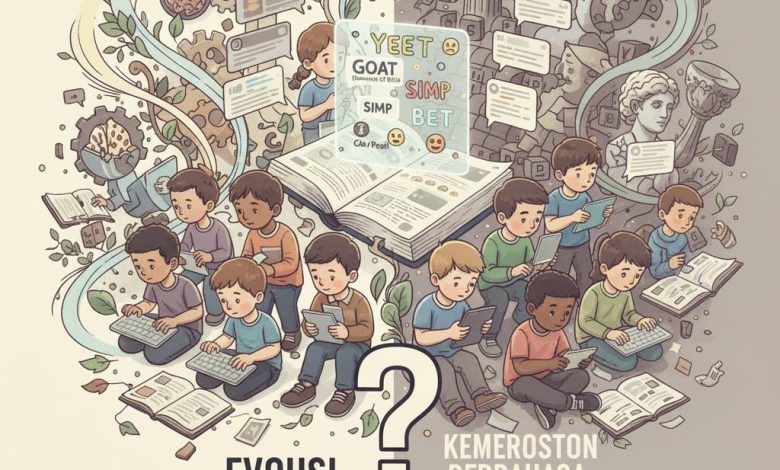
Oleh: Athaya Hanun Sasmitha, Mahasiswa Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi (FSBK) Universitas Ahmad Dahlan
PWMJATENG.COM, Bahasa selalu bergerak mengikuti zamannya. Kini, di era dominasi media sosial dan budaya digital, Generasi Alpha—mereka yang lahir setelah 2010—muncul dengan “kamus bahasa baru” yang lahir dari dunia daring. Istilah seperti rizz, slay, vibes, atau ngabers menjadi bagian dari percakapan sehari-hari. Lalu, apakah fenomena ini merupakan tanda evolusi bahasa atau kemerosotan berbahasa?
Menurut prinsip Sapir-Whorf, bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan jendela cara berpikir manusia. Cara kita memilih kata dapat membentuk cara kita memandang realitas. Dalam konteks ini, dominasi slang dan istilah digital yang digunakan Generasi Alpha bisa memengaruhi cara mereka menafsirkan dunia di sekitar.
Generasi ini tumbuh di tengah arus informasi yang luar biasa cepat. Dalam hitungan detik, mereka dapat mengakses segala hal—dari hiburan hingga pengetahuan—melalui layar ponsel. Akibatnya, mereka cepat beradaptasi dengan istilah baru dan menciptakan pola komunikasi instan yang selaras dengan ritme digitalisasi.
Bahasa Generasi Alpha sesungguhnya dapat dilihat sebagai bentuk evolusi linguistik. Dari perspektif ini, munculnya “kamus bahasa baru” justru menandakan kreativitas dan keberanian mereka mengekspresikan identitas. Mereka tidak hanya meminjam kosakata asing, tetapi juga memberi makna baru dan menyesuaikannya dengan konteks budaya lokal.
Ahli linguistik David Crystal menyebut, perubahan bahasa adalah hal alami. Menurutnya, kekhawatiran terhadap “kemerosotan bahasa” sering kali muncul karena nostalgia terhadap bentuk lama. Faktanya, bahasa hanya beradaptasi terhadap kebutuhan komunikasi generasi baru.
Contohnya, istilah “rizz” (turunan dari charisma) mencerminkan kemampuan kognitif generasi muda dalam memadatkan makna dan menciptakan simbol identitas sosial yang khas. Sebuah studi internal TikTok Indonesia (2023) bahkan menunjukkan bahwa 92% istilah slang baru di Indonesia terbentuk melalui code-mixing atau pemadatan kata—bukti bahwa efisiensi dan ekspresi diri menjadi nilai utama dalam komunikasi digital.
Namun, di sisi lain, fenomena ini juga mengandung risiko. Salah satunya adalah brain rot—istilah populer untuk menggambarkan menurunnya kapasitas fokus dan daya pikir akibat paparan media digital berlebih. Ketika bahasa yang digunakan terus menerus bersifat instan dan terpotong, kemampuan berpikir logis dan argumentatif bisa ikut tergerus.
Noam Chomsky mengingatkan bahwa meskipun kemampuan berbahasa bersifat bawaan (universal grammar), kompleksitas pola pikir sangat bergantung pada struktur dan kekayaan bahasa yang digunakan. Jika Generasi Alpha terbiasa dengan kalimat pendek, emoji, atau kata yang disingkat, maka mereka berpotensi kehilangan kemampuan bernalar dalam bentuk bahasa formal yang lebih kompleks.
Perubahan bahasa yang dialami Generasi Alpha sebetulnya tidak sepenuhnya baik atau buruk. Ia adalah proses alami dalam revolusi digital yang membawa transformasi linguistik dan sosial sekaligus. Tantangannya adalah menjaga agar evolusi ini tidak mengikis kemampuan bahasa formal dan literasi kritis.
Peran orang tua menjadi penting untuk menyeimbangkan komunikasi digital dan interaksi nyata. Dorongan untuk berbicara tatap muka, berdiskusi, atau membaca buku dapat membantu anak mengasah kepekaan berbahasa. Pendekatan reward–punishment yang disertai kasih sayang juga dapat memperkuat motivasi mereka untuk berbahasa dengan baik tanpa merasa ditekan.
Demikian pula, pendidik harus adaptif. Mereka perlu memahami konteks bahasa gaul dan kapan penggunaannya bisa dialihkan ke bentuk yang lebih formal. Pembelajaran bahasa Indonesia seharusnya mengajarkan fleksibilitas konteks—bukan sekadar benar atau salah.
Masyarakat pun berperan besar. Kita dapat memperkaya bahasa Indonesia dengan istilah baru di bidang sains, teknologi, dan budaya, agar tetap menjadi bahasa ilmu pengetahuan dan kemajuan. Dengan begitu, bahasa Indonesia tidak akan tertinggal oleh dinamika global, tetapi menjadi fondasi literasi digital yang kuat.
Fenomena “kamus bahasa baru” pada Generasi Alpha bukan semata gejala kemerosotan, melainkan refleksi zaman yang sedang berubah. Bahasa adalah cermin pikiran, dan perubahan bahasa menunjukkan cara baru manusia berpikir, berkomunikasi, dan membangun identitas.
Yang terpenting bukan menolak perubahan, melainkan mengarahkan evolusi bahasa agar tetap berpijak pada nilai literasi, logika, dan kemanusiaan.
Editor: Al-Afasy