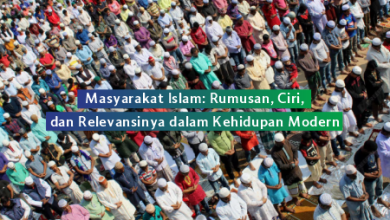“Serakahnomics” dan Gurita Perekonomian Indonesia: Mengurai Insentif, Oligarki, dan Jalan Pembenahan

PWMJATENG.COM – Istilah “Serakahnomics” bukan istilah resmi dalam kamus ekonomi, tetapi pas sekali menggambarkan pola ketika keputusan ekonomi dan politik digerakkan oleh nafsu rente ketimbang produktivitas: mengejar laba cepat lewat akses istimewa, regulasi yang “menguntungkan yang sudah kuat”, dan jejaring yang menutup pintu persaingan sehat. Dalam konteks Indonesia, gurita ini tampak dalam aneka bentuk: kartel harga, lisensi yang langka, kuota impor-ekspor yang mudah “dibisniskan”, hingga penguasaan sumber daya alam yang manfaatnya bocor sebelum sampai ke publik.
Pertama, mari bicara insentif. Ekonomi pasar pada dasarnya bertumpu pada insentif—“tangan tak terlihat” Adam Smith—yang idealnya mendorong inovasi dan efisiensi. Namun Smith juga mengingatkan bahwa pelaku usaha bisa bersekongkol untuk membatasi persaingan. Di sinilah “Serakahnomics” bercokol: ketika biaya berkolusi dan melobi lebih murah dibanding berinvestasi pada riset, kualitas, atau efisiensi. Anne Krueger menyebutnya rent seeking: mengalihkan energi dari mencipta nilai (value creation) ke perebutan nilai (value capture) melalui pintu regulasi. Gordon Tullock menunjukkan mengapa aktivitas seperti ini persisten: imbalannya privat, biayanya disebar ke publik—konsumen menanggung harga mahal, negara kehilangan pajak, inovasi mandek.
Kedua, asimetri informasi. Joseph Stiglitz menekankan bahwa pasar nyata jarang sempurna; informasi tidak seimbang melahirkan perilaku oportunistik. Dalam beberapa komoditas strategis—pangan, energi, logistik—akses data pasokan-permintaan dan “isu lapangan” sering terkonsentrasi pada segelintir aktor. Ketika informasi jadi komoditas politik, kebijakan rawan disetir untuk mengukuhkan posisi dominan: tender disusun “pas ukuran”, standar mutu digeser-geser, atau jadwal distribusi diatur agar pesaing selalu terlambat.
Ketiga, struktur pasar dan regulasi persaingan. Oligopoli yang tidak diawasi ketat memudahkan pembentukan kartel harga—eksplisit maupun diam-diam. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) punya mandat menindak, tetapi gurita “Serakahnomics” kerap bergerak lebih lincah: menggunakan perusahaan cangkang (beneficial ownership disamarkan), memecah entitas agar lolos ambang pelaporan, atau menempatkan orang-orang kunci di posisi strategis (regulatory capture). Mancur Olson menyebut dinamika ini sebagai “koalisi distributif”—kelompok kecil yang terorganisasi baik mampu memengaruhi kebijakan melawan kepentingan publik yang tersebar.
Baca juga, Hidup sebagai Ujian: Menemukan Keseimbangan dalam Ibadah dan Kehidupan
Keempat, institusi dan politik ekonomi. Daron Acemoglu dan James Robinson membedakan institusi inklusif—yang membuka akses kesempatan—dengan institusi ekstraktif—yang menyalurkan sumber daya pada elite. “Serakahnomics” tumbuh subur di ekosistem ekstraktif: aturan dibuat lentur untuk yang dekat kekuasaan, sementara pelaku UMKM dan startup menghadap tembok tinggi biaya kepatuhan, perizinan rumit, dan pembiayaan mahal. Hasilnya dapat ditebak: konsentrasi kekayaan makin menebal, sebagaimana diperingatkan Thomas Piketty bahwa ketika imbal hasil modal (r) konsisten melampaui pertumbuhan (g), ketimpangan melebar—terutama jika pajak dan tata kelola lemah.
Kelima, sumber daya alam dan tragedi tata kelola. Elinor Ostrom menunjukkan bahwa pengelolaan “milik bersama” bisa efektif bila ada aturan jelas, penegakan kolektif, dan transparansi. Di Indonesia, dari hulu tambang hingga hilir tata niaga, kebocoran muncul ketika konsesi longgar, pengawasan lemah, dan publik tak bisa menelusuri aliran manfaat. “Serakahnomics” di sektor SDA bukan sekadar korupsi transaksional; ia struktural—mengunci pembaruan teknologi, memiskinkan daerah penghasil, dan memindahkan risiko lingkungan kepada masyarakat.
Apa akibat makro dari semua itu? Produktivitas total faktor tertahan; biaya logistik tinggi; inovasi rendah; kepercayaan publik tergerus. Kesemuanya menekan kelas menengah, mempersempit mobilitas sosial, dan pada gilirannya mengerdilkan pasar domestik yang sebetulnya potensial. Ekonomi tumbuh, tetapi rapuh—mudah terguncang isu pasokan, harga, atau kebijakan yang berubah seketika.
Lalu, bagaimana membenahinya? Ada lima tuas kebijakan yang saling menguatkan.
- Transparansi kepemilikan dan data pasar. Wajibkan pengungkapan pemilik manfaat (beneficial ownership) yang dapat ditelusuri publik. Buka data perizinan, kuota, dan realisasi impor-ekspor secara waktu-nyata. Ketika sinar matahari masuk, biaya kolusi naik drastis.
- Penegakan persaingan dan antikartel. Perkuat kewenangan, anggaran, dan teknologi penegakan KPPU; dorong analitik forensik data transaksi untuk mendeteksi pola penetapan harga yang janggal. Sanksi harus menyakitkan: denda proporsional pada laba ilegal, larangan direksi, hingga remediasi struktural (divestasi bila perlu).
- Reformasi pajak dan anti-erosion. Tindak penghindaran pajak lintas yurisdiksi; gunakan pelaporan negara per negara (CbCR), e-faktur yang terhubung, dan audit berbasis risiko. Pajak kekayaan dan properti bernilai tinggi yang efektif memperlambat konsentrasi modal tanpa memukul usaha produktif.
- Pendanaan kompetitif bagi UMKM dan inovator. Turunkan biaya modal lewat penjaminan kredit berbasis data alternatif, skema pembagian risiko, dan pasar modal yang ramah emiten kecil. Ketika pesaing baru mudah muncul, “rente lama” tergerus oleh dinamika pasar.
- Integritas kebijakan dan pintu putar. Atur “cooling-off period” bagi pejabat yang pindah ke industri yang ia awasi; perkuat pelaporan konflik kepentingan dan perlindungan pelapor (whistleblower). Ketika pintu putar berdesing pelan, peluang tangkap-regulasi mengecil.
Pada akhirnya, melawan “Serakahnomics” bukan soal antipasar; justru sebaliknya—ini perjuangan memulihkan pasar agar kembali melayani publik, bukan segelintir pihak. Pasar yang sehat memerlukan hukum yang tegas, institusi yang akuntabel, serta warga yang kritis. Jika lima tuas tadi bekerja bersama, kita bukan hanya membongkar gurita, tetapi juga menumbuhkan ekosistem ekonomi Indonesia yang kompetitif, adil, dan tahan guncangan.
Referensi
Adam Smith, The Wealth of Nations (1776) & The Theory of Moral Sentiments (1759) – persaingan dan dimensi moral pelaku pasar.
Anne O. Krueger (1974), “The Political Economy of the Rent-Seeking Society,” American Economic Review – teori rent seeking.
Gordon Tullock (1967), “The Welfare Costs of Tariffs, Monopolies, and Theft,” Western Economic Journal – biaya sosial rente.
Joseph E. Stiglitz (2001), Nobel Lecture & karya tentang asimetri informasi – kegagalan pasar dan informasi.
Daron Acemoglu & James A. Robinson (2012), Why Nations Fail – institusi inklusif vs ekstraktif.
Thomas Piketty (2014), Capital in the Twenty-First Century – ketimpangan r > g.
Elinor Ostrom (1990), Governing the Commons – tata kelola sumber daya bersama.
Mancur Olson (1982), The Rise and Decline of Nations – koalisi distributif dan inersia kebijakan.