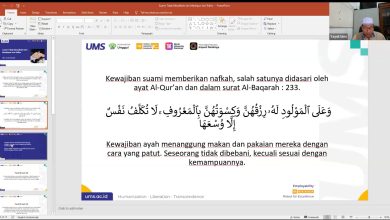Pandangan Muhammadiyah tentang Perempuan (1)

Oleh : Dr. KH. Tafsir, M.Ag.*
PWMJATENG.COM – Kadang agama menjadi institusi dalam dilema (Hendropuspito, 1983 : 127). Sebab dalam kenyataannya, agama sering tidak hanya berhadapan dengan kesulitan yang dengan cara tertentu dapat dipecahkan, tetapi juga berhadapan dengan persoalan yang pelik sehingga dijawab “ya” salah, dijawab “tidak” juga tidak benar. Ibarat makan buah simalakama, dimakan mati bapak, tidak dimakan mati ibu.
Di antara dilema agama adalah di satu pihak harus menjaga atau mempertahankan otentisitas teks kitab sucinya, di pihak lain harus berhadapan dengan perkembangan zaman. Dalam beberapa kasus teks agama (Al-Qur’an dan Sunnah) seperti “ketinggalan” zaman atau tidak “nyambung” dengan kenyataan kultural masyarakat tertentu. Kepemimpinan perempuan misalnya, apa yang diragukan dari kemampuan perempuan jadi pemimpin. Kenyataannya QS. An-Nisa : 34 sering dijadikan vonis tidak kebolehannya, diperkuat hadis-hadis yang bernuansa misogini. Demikian juga dengan kasus poligami, tak ada yang ragu akan kebolehannya secara tekstual, tetapi secara sosio-kultural–yang sebenarnya juga memiliki landasan teologis- sulit untuk diterima. Tidak mengherankan jika menyangkut isu-isu tentang kedudukan perempuan dalam Islam selalu menarik dan kadang tidak pernah tuntas, termasuk dalam Muhammadiyah.
Sebagai dilema, pembahasan tentang beberapa kasus atau persoalan perempuan mengalami jalan buntu sehingga dimauqufkan, seperti kasus wanita bepergian dalam Himpunan Putusan Tarjih : 295. Dimauqufkan karena hujjah antara yang melarang dan membolehkan sama kuatnya. Dalam fakta sosiologisnya, sesuai perkembangan zaman, hampir tidak mungkin jika seorang perempuan selalu didampingi mahromnya dalam setiap bepergian. Kasus serupa, jika tidak mauqufpun, keputusannya tetap debatable.
Belum lagi, jika Al-Qur’an dan Sunnah jika dipahami secara puritan mungkin akan “berwajah Arab”. Misalnya, al-Qur’an begitu perhatian menyoroti persoalan anak “yatim”, yang diartikan sebagai seorang anak manusia yang belum dewasa ditinggal wafat ayahnya. (M. Quraish Shihab, 2002 : 547). Bagaimana nasib anak yang ditinggal ibunya, tidak memerlukan perhatian? Tidak pentingkah seorang ibu, sehingga tidak masalah bagi anaknya yang belum dewasa jika ditingalkannya? Sementara banyak anak yang kemudian menjadi korban ibu tirinya. Terlebih lagi jika dalam suatu rumah tangga justru ibunyalah yang dominan menafkahi keluarganya.
Baca juga, Setengah Abad Salat Id di Lapangan
Banyak tokoh baik dari kalangan perempuan sendiri seperti Fatima Mernissi maupun para pakar kesetaraan gender mencoba untuk membuat reinterpretasi yang lebih kontekstual terhadap teks-teks yang bernuansa misogyny, seperti kasus kepemimpinan perempuan, waris, poligami, tetapi pada saat yang sama reaksi sebaliknya akan muncul. Kesemuanya menjadi persoalan yang jawabannya tak pernah bulat.
Sebagai paham Islam yang berkemajuan Muhammadiyah harus memiliki keberanian mengambil keputusan terkait persoalan perempuan. Wajah Islam puritan Muhammadiyah tetaplah yang moderat, mengikuti perkembangan zaman dan kultural. Untuk ini diperlukan landasan, wawasan dan perangkat yang memadai sehingga keputusan yang diambil tidak asal berani, tetapi sangat argumentatif dan komprehensif.
Landasan Normatif dan Teologis Perempuan dalam Muhammadiyah
Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah memberi ruang yang cukup “maju” bagi perempuan untuk berkiprah di ruang publik. KH. Ahmad Dahlan tampaknya sadar betul akan pentingnya memajukan kaum perempuan, sebelum akhirnya mendirikan Aisyiyah. Sebagai awal langkahnya beliau merekrut enam “Siti” sebagai kader inti yang akan dijadikan pimpinan Aisyiyah kelak. Keenam perempuan tersebut adalah Siti Barijah, Siti Dawimah, Siti Dalalah, Siti Busjro, Siti Wadingah dan Siti Badilah. Dalam perjalanannya, keenam “Siti” inilah menjadi pimpinan inti Aisyiyah yang pertama dengan Siti Barijah dan Siti Badilah sebagai ketua dan sekretaris. (Alfian, 1989 : 172).
Melihat kepedulian KH. Ahmad Dahlan dalam memberi ruang kepada perempuan di ranah publik, menunjukkan bahwa corak teologi Muhammadiyah sangatlah progresif dan inklusif jauh dari corak puritan dan eksklusif sebagaimana corak teologi salaf dengan acuan pokok kitabnya pada Aqidah al-Wasithiyah-nya Ibn Taimiyah (661 H/1263 M-728 H/1328 M) dan Kitab at-Tauhid-nya Syaikh Muhammad ibn Abd al-Wahab (1115 H/1702 M-1206 H/1792 M). yang lebih berkonsentrasi pada pemurnian aqidah. Jika direnungkan, kepedulian Dahlan telah membawa perempuan pada peran yang luas di wilayah kultural dan sosial terbebas dari pengucilan dan subordinasi sebagaimana harapan kaum feminis. (Neng Dara Affiah, 2011 : 175).
Bisa jadi semangat progresif KH. Ahmad Dahlan lebih banyak terilhami oleh teologi Syaikh Muhammad Abduh (1265 H/1849 M-1323 H/1905 M). Terlepas dari kebetulan atau memang beliau terpengaruh Abduh, QS. Ali Imran : 104 yang menjadi inspirasi berdirinya Muhammadiyah, dibahas oleh Abduh dalam Risalah at-Tauhid-nya. QS. Ali Imran 104 ini mendorong umat Islam untuk at-ta’lim, irsyad al-‘amah dan al-amr bi al-ma’ruf wa an-nahy ‘an al-maukar. (Al-Imam Muhammad Abduh, 1986 : 93). Berbeda dengan Abduh yang tampil sebagai intelektual dengan produktifitas yang terekspresikan dalam tulisan dengan kitab-kitabnya, Dahlan tampil menjadi pelaku dan aplikator yang tak mengenal lelah. (Alfian, 1989 : 151). Abduh tampil dengan buku, maka Dahlan tampil dengan organisasi dan amal nyata. Atas dasar itulah Alfian menyebut Dahlan sebagai the pragmatist yang slowly but sure.
*Ketua PWM Jawa Tengah. Doktor Bidang Islamic Studies UIN Walisongo Semarang.
Editor : M Taufiq Ulinuha