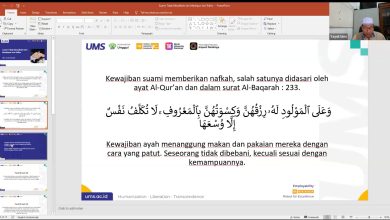Isra Mi’raj: Metanarasi Makna di Tengah Krisis Peradaban

Oleh : Ardian Yuniarko, S.E.,M.M. (Branding Consultant, Pegiat UMKM Sayuran, Pengurus LP-UMKM PWM Jateng)
PWMJATENG.COM, Isra Mi’raj sering diperingati sebagai peristiwa sakral yang menggetarkan iman, namun jarang dibaca sebagai teks kritik peradaban. Padahal, di tengah krisis etika politik, ketimpangan ekonomi, dan banalitas kekuasaan hari ini, Isra Mi’raj justru menawarkan metanarasi makna yang relevan dan subversif.
Isra Mi’raj bukan sekadar kisah Rasul yang naik ke langit, melainkan peringatan keras bahwa peradaban yang kehilangan orientasi spiritual akan runtuh oleh kesombongannya sendiri.
Isra (perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Bayt Al Maqdis) adalah simbol keterikatan Islam pada realitas sosial dan geopolitik. Bayt Al Maqdis bukan ruang kosong; ia berada di wilayah konflik, penindasan, dan perebutan kekuasaan. Artinya, sejak awal Islam menegaskan bahwa iman tidak netral terhadap ketidakadilan.
Dalam konteks Indonesia hari ini, Isra menantang praktik politik yang menjadikan agama sekadar ornamen elektoral. Ketika simbol-simbol religius dipakai untuk legitimasi kekuasaan namun abai pada keadilan sosial, maka yang terjadi bukan Isra, melainkan eksploitasi iman.
Mi’raj adalah perjalanan vertikal (simbol bahwa kekuasaan, ilmu, dan teknologi harus tunduk pada nilai transendental). Dalam Mi’raj, Nabi tidak membawa pulang mandat politik, previlege ekonomi, atau hak istimewa elite, melainkan shalat yang merupakan pembiasaan disiplin moral dan kesadaran etis.
Ini kritik telak bagi elite hari ini. Kekuasaan tanpa Mi’raj melahirkan keserakahan, kebijakan tanpa nurani, dan pembangunan yang mengorbankan manusia. Ketika pertumbuhan ekonomi dijadikan mantra, tetapi kemiskinan struktural dibiarkan, maka negara sedang bergerak horizontal tanpa arah vertikal.
Shalat sering direduksi menjadi urusan privat, padahal ia adalah produk langsung dari peristiwa kosmik Isra Mi’raj. Shalat mendidik keteraturan, kejujuran waktu, egaliter (tanpa kelas dalam saf), dan akuntabilitas.
Jika shalat benar-benar dipahami sebagai hasil Mi’raj, maka korupsi adalah bentuk kegagalan spiritual, bukan sekadar pelanggaran hukum. Ketidakadilan sosial adalah tanda putusnya hubungan langit dan bumi.
Bangsa ini menghadapi krisis bukan karena kekurangan regulasi, tetapi kehilangan metanarasi makna. Agama terjebak seremoni, politik kehilangan moral, dan ekonomi berjalan tanpa empati.
Isra Mi’raj mengingatkan bahwa peradaban besar selalu dibangun oleh mereka yang mampu menghubungkan langit dan bumi (nilai dan kebijakan, iman dan keberpihakan).
Isra Mi’raj bukan kisah nostalgia teologis, melainkan peringatan historis. Bangsa yang hanya bergerak cepat secara horizontal (membangun infrastruktur, teknologi, dan kekuasaan) tanpa keberanian untuk Mi’raj, akan kehilangan arah dan makna.
Pertanyaannya sederhana namun menentukan:
apakah kita sedang naik untuk menjadi manusia yang lebih adil, atau hanya berlari tanpa tujuan menuju kelelahan kolektif?
Isra Mi’raj telah memberi peta. Tinggal keberanian kita untuk membacanya sebagai kritik, bukan sekadar perayaan.